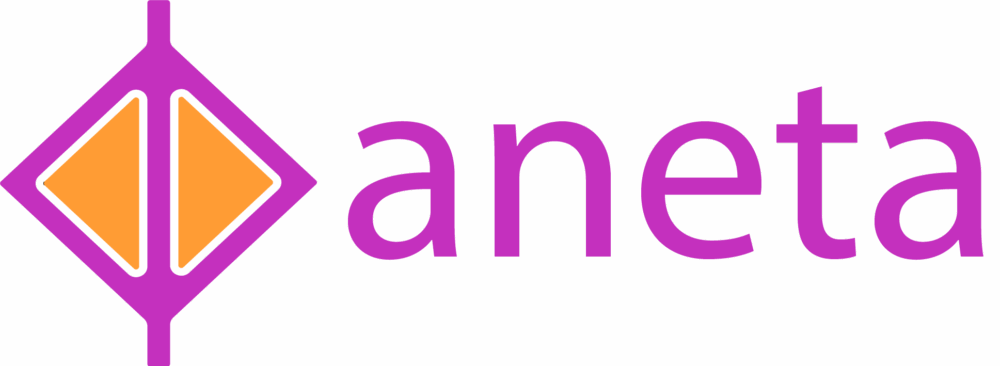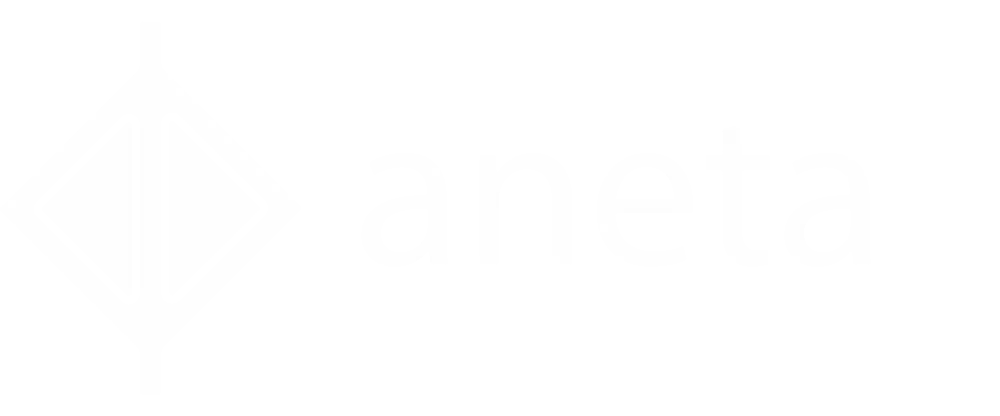Oleh: Sekar Banjaran Aji
Ada banyak pohon yang tetap hidup tanpa daun tapi mustahil ada pohon yang hidup tanpa akar. Kalimat itu saya dapatkan dari Kakek yang begitu menyayangi saya dan selalu mendongengkan kisah pewayangan sepulang sekolah pada saya. Kakek dari suku Jawa, beranak pinak dengan perempuan Jawa, dan singkat cerita menghadirkan saya yang sepenuhnya lahir sebagai perempuan Jawa. Saat ditugasi advokasi di tanah Papua, saya menangis karena saya tidak tahu apa-apa soal Papua dan barangkali selamanya saya tidak pernah tahu apa-apa soal Papua.
Sebagai Perempuan Jawa, rasanya tidak ada cara lain selain belajar soal Papua, baik dari buku, diskusi dengan teman atau bertanya langsung pada Orang Asli Papua. Pada sebuah momen saya bertemu dengan buku Linda Tuhiwai Smith berjudul “Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples”. Linda Tuhiwai Smith memberi pengetahuan bahwa penelitian sebagai alat kolonisasi merupakan kritik yang kuat terhadap bagaimana tradisi akademis Barat secara historis telah digunakan untuk mengendalikan, mendefinisikan, dan meminggirkan masyarakat adat. Penelitian kolonial seringkali memperlakukan komunitas adat sebagai objek studi—mengekstraksi pengetahuan tanpa persetujuan atau manfaat. Lebih jauh, hasil penelitian tadi sering digunakan untuk membenarkan kebijakan asimilasi, perampasan tanah, dan penghapusan budaya. Meski penelitian yang bermaksud baik pun dapat melanggengkan kekerasan epistemik jika mengabaikan pandangan dunia dan nilai-nilai adat.
Secara praktik, Linda Tuhiwai Smith memberikan contoh melalui Penelitian Kaupapa Māori: Sebuah Alternatif Dekolonial yang dikembangkan oleh para cendekiawan Māori. Secara sederhana penelitian Kaupapa Māori merupakan karya dari Māori, untuk Māori, dan untuk Māori. Penelitian ini berpusat pada filosofi, bahasa, dan praktik budaya Māori sebagai fondasi penelitian. Menekankan penentuan nasib sendiri, etika relasional, dan manfaat kolektif. Sebuah argumen solid yang sulit saya praktikan karena saya bukan bagian dari komunitas adat. Saya secara sadar memahami bahwa saya bisa jadi menjadi bagian dari ‘orang Barat’ yang gagasannya seringkali bermasalah ketika melihat masyarakat adat secara umum atau masyarakat Papua secara khusus.
Meletakan pengalaman dalam bekerja yang baru seumur jagung ini, membuat saya sadar bahwa metodologi dekolonisasi memerlukan lebih dari sekadar perubahan alat penelitian—melainkan menuntut perubahan strategis dalam kekuatan, tujuan, dan perspektif. Saya tertarik merefleksikan kerja saya mendampingi masyarakat Adat Awyu berjuang demi menyelamatkan hutan alam kering yang luasnya 26.326 hektare atau lebih dari sepertiga luas DKI Jakarta. Kerja tersebut tidak mudah karena Masyarakat Awyu yang dulunya belum, kini berkesempatan menggunakan jalur hukum dan kampanye publik untuk merebut kembali suara mereka—mengubah litigasi menjadi bentuk perlawanan epistemik.
Praktik Dekolonial
Pasca proklamasi, terjadi peralihan kedaulatan dari kelas kolonial kepada rakyat Indonesia sendiri. Kelas sosial yang pada masa Hindia Belanda digolongkan sebagai “pribumi” kini memiliki kekuasaan membentuk hukum (Hamidi, 2016). Sementara di dalam kewargaan Indonesia yang diidealkan seragam itu, masih terdapat kolektfkolektf masyarakat adat yang jati dirinya tak dapat dilebur secara sembarangan (Soepomo,1979). Di satu sisi, anggota masyarakat adat seketika dianggap sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, individu per individu. Namun, keanggotaan mereka di dalam kolektf dengan tata hukum tersendiri yang berdaulat di hadapan hukum formal negara, adalah kenyataan lain yang tak boleh dikesampingkan (Francois Robert Zacot, 2008).
Hal yang terjadi di Tanah Papua tidak kalah mengerikan, Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 14 Juli 1969 menjadi awal bergabungnya Papua menjadi bagian Indonesia. Pepera, dengan proses yang dianggap tidak demokratis oleh rakyat Papua karena tidak ada pelibatan yang bermakna dari rakyat Papua. Selanjutnya hasil Pepera telah merusak legitimasi hukum adat dalam menentukan nasib tanah dan wilayah adat di Papua.
Sampai sejauh ini, negara mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisional yang mereka miliki secara konstitusional pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peraturan tersebut kemudian dipertegas dengan Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengakui hutan di wilayah masyarakat adat sebagai hutan milik mereka dan bukan milik negara. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menguji pasal-pasal dalam UU Kehutanan juga menegaskan bahwa hutan yang berada di dalam daerah tempat tinggal masyarakat adat adalah hutan adat sehingga pemanfaatannya tidak bisa semena-mena dan harus memperhatikan masyarakat adat yang tinggal di situ. Selain itu, khusus untuk daerah Papua, terdapat Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat MHA Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Adat Atas Tanah yang dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa dalam pemanfaatan tanah dan pengalihan hak, setiap pihak harus memperoleh persetujuan tertulis masyarakat adat.
Namun dalam keseharian, banyak tanah adat masyarakat adat Papua yang kemudian diklaim sebagai milik negara dan diberikan kepada korporasi untuk kepentingan pembangunan, yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Sehingga perjuangan hukum di Papua bukan hanya terkait lingkungan—melainkan tindakan dekolonial. Dengan menggugat perusahaan kelapa sawit dan pemerintah, para penggugat dari masyarakat adat menegaskan kedaulatan tanah, mempertahankan ekosistem, dan membingkai ulang keadilan iklim melalui pandangan dunia masyarakat adat.
Contohnya Greenpeace Indonesia mencatat, sepanjang 2001-2023, hutan Papua mengalami deforestasi seluas 722.256 hektare, menyisakan 84.594.197 hektare hutan yang tersisa. Selain itu Greenpeace Indonesia juga mendokumentasikan perubahan bentang alam Papua, khususnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel, perluasan perkebunan kelapa sawit, dan eksploitasi hutan adat. Pulau-pulau kecil di Raja Ampat yang dulunya indah kini terancam hilang karena eksploitasi tambang. Hal ini sebenarnya menggambarkan bahawa situasi Papua sebagai krisis sosio-ekologis, di mana kepentingan pasar global berbenturan dengan ekosistem lokal dan hak-hak masyarakat adat. Hal ini sejalan dengan kritik Smith terhadap epistemologi Barat yang mengabaikan dimensi relasional dan spiritual tanah. Perbedaannya kini, Indonesia diduga menjadi tangan barat yang sedang mengekstraksi Papua.
Penyebaran viral “All Eyes on Papua” sebagai respon simpatik perjuangan Suku Awyu dan Moi mencerminkan solidaritas transnasional, serupa dengan gerakan “All Eyes on Rafah.” Ini adalah bentuk kerja memori dekolonial, merebut kembali sejarah dan melawan penghapusan melalui perhatian dan tindakan kolektif.
Namun masih ada beberapa catatan mengapa kerja tersebut masih jauh dari kata ideal. Salah satunya kegagalan menjemput kemenangan dari Mahkamah Agung yang hingga kini masih membelenggu masyarakat Suku Awyu. Lantas cerita litigasi iklim seperti apa yang bisa membebaskan masyarakat adat Papua dari belenggu kolonialisme gaya baru bernama ekstrativisme?
Penulis: Sekar Banjaran Aji adalah seorang advokat lingkungan dan Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia. Saat ini, ia juga menjabat sebagai Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) Indonesia. Sekar memiliki latar belakang sebagai pengacara dan aktif dalam isu-isu lingkungan, terutama terkait dengan litigasi iklim dan ekologi politik feminis.