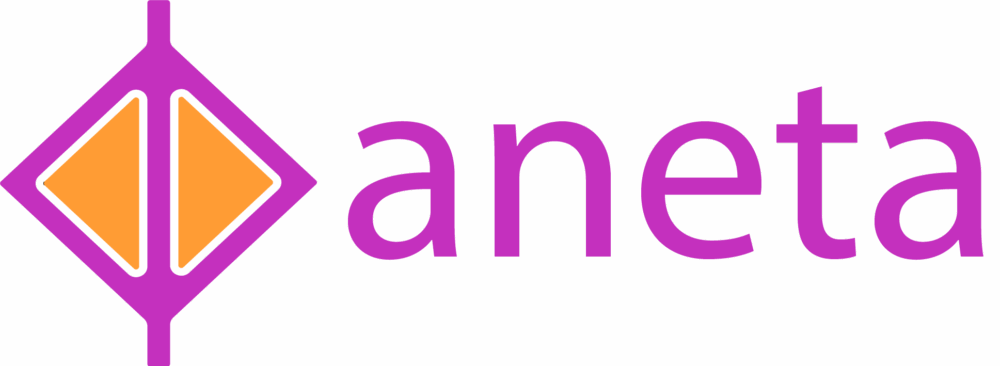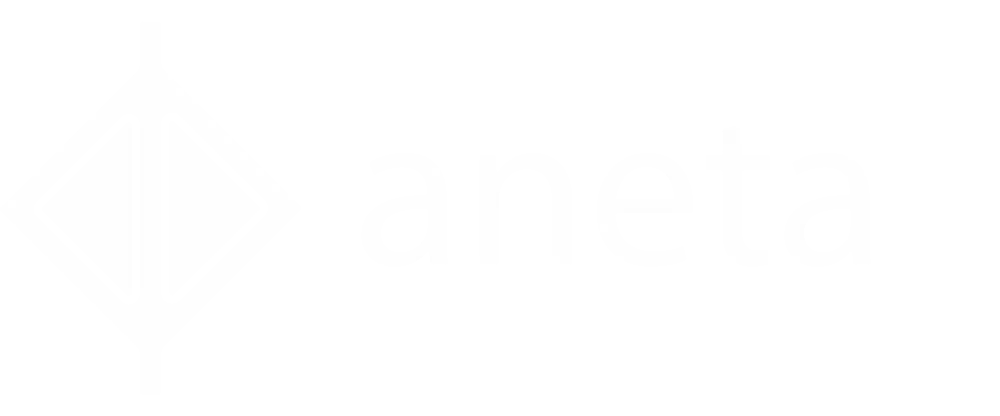Oleh: Sellina Aurora
Pengantar
Di suatu festival anak pada Hari Anak Nasional, saya duduk menikmati keindahan senyum dan euforia bahagia anak-anak yang riuh, berlari, melompat, tertawa tanpa beban. Rasanya damai dan tenang sekali, menelisik masa kecil dalam ingatan pada tubuh dewasa yang penat dan penuh beban. Menyenangkan melihat anak-anak dapat merayakan masa kecil mereka yang lebih dari pantas untuk bermain dan bersenang-senang.
Namun seketika, angan ini melayang membayangkan gambar-gambar yang berseliweran di media sosial: anak-anak yang terjebak dalam reruntuhan di Gaza, atau yang bersembunyi di balik semak di Intan Jaya, tempat di mana bunyi tawa digantikan derap sepatu tentara dan dentuman senjata.
Palestina dan Papua, dua wilayah yang berbeda secara geografis, namun seolah menyatu dalam luka yang sama: tanah-tanah yang terus diguncang konflik politik dan kekerasan bersenjata, di mana anak-anak menjadi korban yang tak sempat memilih. Mereka kehilangan rumah, keluarga, pendidikan, dan bahkan hak paling mendasar: hak untuk hidup damai.
Dalam teologi kristen, dosa negara kepada anak-anak tercatat di kitab suci, yakni Musa yang harus diselamatkan dari pembantaian massal bayi Ibrani oleh Firaun, juga Yesus yang dibawa mengungsi ke Mesir untuk menghindari kekejaman Herodes. Nyatanya anak-anak hari ini pun masih terus diburu oleh ketakutan yang sama yaitu ketakutan penguasa yang takut kehilangan kuasa, lalu menghancurkan yang paling lemah.
Yesus berkata di dalam alkitab, “Biarkan anak-anak itu datang kepada-Ku…” (Markus 10:14). Tapi bagaimana mereka akan datang jika jalannya diblokade, jika tubuh mereka hancur oleh bom atau bahkan berlumuran karena peluru, atau jika hidup mereka direduksi hanya menjadi statistik konflik?
Tubuh-Tubuh Kecil dalam Perang yang Bukan Milik Mereka
Film dokumenter produksi Jubi, berjudul Sa Pu Nama Pengungsi, menggambarkan secara nyata dan menyentuh kehidupan anak-anak pengungsi dari Nduga dan Maybrat, Papua. Dengan sudut pandang dua anak yang diberi nama “Pengungsi,” karena mereka lahir dan tumbuh di tengah hutan, di tenda-tenda darurat, dan di bawah ancaman senjata. Film ini mengungkap wajah kemanusiaan yang sering luput dari perhatian: tubuh-tubuh kecil yang direnggut dari masa kanak-kanak mereka, dipaksa menjadi bagian dari perang yang sama sekali bukan milik mereka.
Sama halnya dengan cerita dari Gaza, cerita ini bukan teori. Pada Mei 2025, dokter pediatrik Alaa al‑Najjar kehilangan sembilan dari sepuluh anaknya dalam satu serangan rumah. Bayi‑bayi kecil dan bocah berumur 12 tahun tewas seketika, sementara ibunya yang justru merawat korban perang menjadi saksi paling pilu atas kehancuran sebuah keluarga. Di sisi lain, dua kakak‑beradik, Karam (9 tahun) dan Lulu (10 tahun), bahkan tewas hanya karena berjalan mengambil air, sebuah tugas yang seharusnya normal bagi anak-anak, tapi di Gaza menjadi jalan maut.
Cerita-cerita tragis ini bukan hanya potret masa kini, tetapi juga melekat dalam sejarah panjang dunia, bahkan direkam dalam kisah-kisah Kitab Suci. Alkitab secara gamblang menggambarkan bagaimana bayi-bayi tak bersalah menjadi korban kekerasan struktural dan ketakutan politik. Ketika Musa lahir, Firaun memerintahkan pembunuhan sistematis terhadap semua bayi laki-laki Ibrani, sebuah genosida yang dibenarkan atas nama stabilitas kerajaan (Keluaran 1–2).
Demikian pula dalam kisah kelahiran Yesus. Ketika Herodes merasa kekuasaannya terancam oleh nubuat tentang “Raja orang Yahudi,” ia memerintahkan pembantaian semua anak laki-laki berusia dua tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya (Matius 2:16–18).
Dua kisah ini menunjukkan satu pola: ketika kekuasaan merasa terancam, tubuh anak-anaklah yang pertama kali dikorbankan. Dan hingga hari ini, pola itu masih terus berulang dari Gaza hingga Papua.
Anak-Anak dalam Cengkeraman Kekuasaan: Tafsir atas Keluaran dan Injil Matius
Dalam tulisannya “Spiritualitas Yokhebed,” Evangelie Pua menyoroti bagaimana kisah dalam Keluaran 1–2 tidak hanya mengisahkan kekejaman Firaun, tetapi juga mengungkap kolusi antara kekuasaan politik, ekonomi, dan agama yang ingin mengontrol hidup dan mati tubuh-tubuh kecil tak berdaya. Firaun, termakan oleh keserakahan dan ketakutan akan kehilangan dominasi, memerintahkan pembantaian sistematis terhadap bayi-bayi laki-laki Ibrani. Ia melihat para bidan bukan sekadar tenaga kesehatan, tapi alat strategis yang bisa dikendalikan untuk memenuhi nafsu kekuasaannya. Ia tahu bahwa para bidan punya kuasa di ujung tangan mereka, dan ia mencoba mengeksploitasi itu.
Namun di tengah sistem yang kejam itu, justru berdiri dua perempuan luar biasa, Sifra dan Pua yang memilih untuk menolak tunduk pada perintah pembunuhan. Mereka menolak menjadi kaki tangan kekuasaan yang menindas. Sebaliknya, mereka menghidupi spiritualitas profetik: mempertahankan kehidupan meski harus melawan instruksi raja.
Evangelie Pua menekankan bahwa tindakan Sifra dan Pua bukan sekadar keberanian sipil, tetapi ekspresi iman, mereka memilih taat pada Allah kehidupan ketimbang pada penguasa maut. Di tengah budaya yang mendewakan stabilitas kekuasaan, mereka menunjukkan bahwa keberpihakan pada anak-anak, pada kelahiran, dan pada masa depan, adalah bentuk spiritualitas yang radikal.
Kisah ini begitu relevan dengan konteks hari ini ketika sistem politik dan militer di banyak tempat memaksakan kehendaknya atas tubuh-tubuh anak-anak: dari pengungsian di Papua, anak-anak yang mati karena kelaparan dan bom di Palestina, hingga para pengungsi kecil yang tak punya akta lahir, tempat tinggal, bahkan nama. Kita membutuhkan Kamerad Sifra dan Pua masa kini, mereka yang dengan segala risiko, tetap berdiri membela kehidupan dan berkata “tidak” kepada sistem yang membunuh.
Sementara itu, dalam bukunya The Ministry of Women in the New Testament, Dorothy Lee menyatakan bahwa narasi pembantaian anak-anak oleh Herodes bukan sekadar tragedi historis, melainkan lambang dari kekerasan struktural negara terhadap yang paling rentan yakni: anak-anak, keluarga miskin, dan tubuh-tubuh yang tak punya kuasa dalam sistem kekaisaran. Herodes, dalam posisinya sebagai penguasa boneka di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi, memilih untuk meredam ancaman lahirnya “Raja Baru” dengan cara membunuh seluruh kemungkinan masa depan.
Yesus, bahkan sebelum bisa berjalan, telah menjadi pengungsi politik. Ia dibawa melarikan diri ke Mesir, tanah yang secara ironis merupakan simbol penindasan masa lalu umat Israel, tempat Musa dulu juga pernah diselamatkan. Dorothy Lee menafsirkan bahwa sejak kelahiran-Nya, Yesus secara eksistensial telah berpihak kepada mereka yang terusir, mereka yang tak diinginkan oleh sistem dominasi. Inkarnasi itu bukan turun di istana atau pusat kekuasaan, tetapi hadir dalam tubuh bayi yang diburu oleh negara.
Melalui penafsiran ini, Lee menunjukkan bahwa kita tak bisa memisahkan spiritualitas Kristiani dari realitas politik tubuh-tubuh yang tertindas. Ia menulis bahwa Injil mengundang pembacanya untuk melihat dunia melalui mata mereka yang paling rentan dan dalam hal ini, mata seorang anak kecil yang melintasi batas negara sebagai pengungsi demi menyelamatkan hidupnya.
Dalam konteks kontemporer, hal ini sangat relevan ketika kita berbicara tentang anak-anak pengungsi dari Maybrat, Nduga, Intan Jaya bahkan Gaza. Mereka bukan sekadar korban kemanusiaan; dalam terang narasi Alkitab, mereka adalah bagian dari tubuh Kristus yang terus disalibkan dalam sejarah.
Allah di Tengah Anak-Anak Pengungsi
Dalam tubuh bayi Musa dan Yesus, yang keduanya hidup sebagai pengungsi sejak kanak-kanak, kita menemukan Allah yang berpihak kepada mereka yang paling rapuh. Bukan di istana, bukan di ruang diplomasi, melainkan di pelukan ibu-ibu yang lari ke hutan, di antara ratapan Rahel, dan dalam ketakutan para bidan yang menolak tunduk pada perintah membunuh. Kitab Suci tidak memisahkan iman dari realitas politik. Sebaliknya, kisah keselamatan justru lahir di tengah ancaman kekuasaan yang menghancurkan kehidupan anak-anak.
Bahagia, bermain, dan belajar adalah hak dasar setiap anak, bukan hadiah, tetapi keharusan yang harus dipenuhi. Setiap orang dewasa, baik sebagai orang tua, pemimpin gereja, pendidik, pejuang dan seharusnya pemerintah juga, maupun bagian dari masyarakat lainnya, memikul tanggung jawab moral dan iman untuk memastikan bahwa hak-hak ini terpenuhi, agar anak-anak dapat tumbuh secara utuh dan meraih masa depan terbaik mereka.
“Setiap anak berharga,” demikian tegas Pdt. Sophie Patty, seorang pendeta perempuan di Papua yang menginisiasi gerakan Sekolah Minggu sebagai ruang edukasi dan perlindungan iman anak-anak dalam gereja-gereja di Tanah Papua
Dan anak-anak yang berharga itu bukan hanya mereka yang duduk manis di sekolah-sekolah kota. Mereka juga adalah Pengungsi Kogoya dan kawan-kawannya, anak-anak yang bertahan hidup di balik perlindungan hutan belantara Intan Jaya, tempat dingin menjadi selimut dan tanah Mama menjadi ranjang. Mereka berharga, bukan karena angka pada data statistik, bukan pula karena belas kasihan sesaat, tapi karena hidup mereka memang layak dihargai dan dijaga.
Dalam banyak kisah yang diwariskan kepada kita, baik dari tradisi agama maupun pengalaman kolektif manusia, anak-anak kerap digambarkan sebagai pusat harapan. Tapi harapan itu tidak tumbuh di ruang hampa. Ia membutuhkan perlindungan, ruang bermain yang aman, makanan yang cukup, pendidikan yang adil, dan lingkungan sosial yang tidak menyakiti mereka.
Tak seharusnya kita terus merayakan Hari Anak di satu tempat, sementara di tempat lain anak-anak masih hidup dalam trauma dan pengungsian. Perayaan tanpa keberpihakan hanya akan menjadi gema kosong dari ketidakadilan yang dibiarkan. Sudah waktunya kita bergerak bersama, bukan sendiri, untuk memastikan setiap anak, di manapun ia berada, bisa merasa aman, bahagia, dan dihargai.
Karena pada akhirnya, ukuran dari kemajuan sebuah bangsa, atau bahkan nilai kemanusiaan kita yang paling dasar, bisa dilihat dari cara kita memperlakukan anak-anak. Seperti kata Eleanor Roosevelt, “Peradaban bisa diukur dari bagaimana kita memperlakukan anak-anak.” Dan hari ini, kita tahu bagi kita di Papua, masih banyak yang harus diperbaiki.
Selamat Hari Anak. Karena semua anak berhak hidup dan tumbuh dengan utuh.